Selangkah yang penghabisan. Dia berhenti berjalan. Menatap segala yang dapat ditatap. Dia melihat langit penuh hiasan cahaya. Kepalanya yang tegak, mulut menganga, pikirannya bermuara kata-kata. Hendak ia membuat sepotong puisi. Namun ia kesusahan, hanya karena tidak punya kemampuan membuat puisi. Ia berusaha memikirkan seperangkat kata-kata. Semakin keras dia berpikir, semakin kesusahan dia mendapatkan kata-kata.
“Telampau banyak jumlah kita-kita. Tapi terlalu sedikit kata-kata.” Senyatanya dia sedang menyinggung kebanyakan manusia (termasuk dirinya sendiri) yang tidak mampu menambah perbendaharaan kata.
Masih pada pemberhentiannya, ia tatap lamat-lamat langit yang penuh hiasan cahaya, kemudian lirih berkata,
“Pada ruang ketiadaan, bercengkrama rindu dan kenangan. Tik! Pada dinding bisunya, detik waktu mendetakkan kesunyian. Hasrat terjebak, nyata tak tersibak!” Spontan sepenggal puisi itu terucap pada bibirnya yang kaku.
“Ahmad...!!! Sudah terlalu malam di luar. Masuklah.”
Suara dari balik pintu rumah itu menyerbu konsentrasinya. Ia sadar, perjalanan tanpa kompas sejak tadi berakhir di depan rumahnya sendiri. Baginya, perjalanan yang berakhir di rumah ini bukan perjalanan biasa. Meski tanpa kompas, itu ditentukan oleh kehendak waktu. Waktu yang kekal, waktu yang tiada penghabisan.
“Cepat masuk, Ahmad. Ibu sudah menunggu sejak tadi.” Kembali suara itu meraung telinganya. Dari balik pintu rumah, kakak perempuan Ahmad menanti dengan cemas.
Ia (Ahmad) melangkah menuju rumah dengan segenap perasaan yang tergantung di langit. Setiap langkahnya diikuti dengan mantra-mantra paling khusyuk.










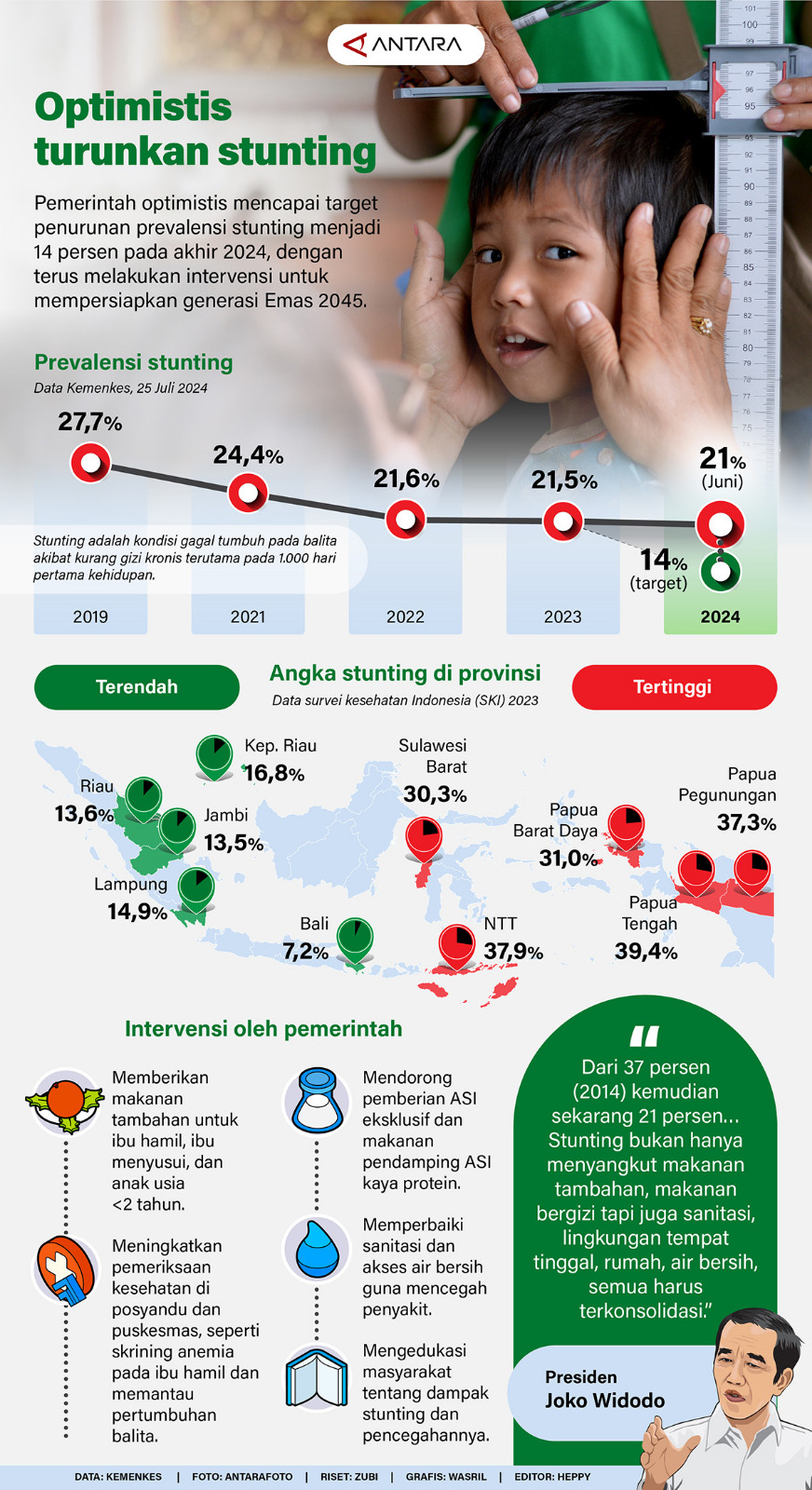

Discussion about this post