MEDIASEMUT.COM – Sedikit keluh malam ini, membekas menjadi kelumit yang melilit saraf ketenangan dan keteduhan di balik loga-loga yang ku tabuh. Sulit untuk melupa pada sekumpul warna yang ku temu di ujung puncak Gamalama di malam tahun baru ini, pelarian sesaat yang ku geluti ini rupanya tak menjerat ku pada sesat. Yang ku dapat hanya teduh beralas doa-doa yang bertengkar di atas langit tuk merebut ijabah tuhan, doa-doa itu senantiasa hadir bersama embun-embun yang yang menyirami gapura lubuk takkala mentari telah pecah di pagi buta.
Sejenak ku wartakan kembali perihal lalu yang tak mudah usang dilibas waktu dan sibuk-sibuk yang terjalani. Iya, perihal puncak berteman sendiri, bertemankan dedaunan dan pohon-pohon perkasa yang bertengger di antara kemiringan yang manandai itu sebagai jurang. Lalu aku puaskan jemari menari beserta dua bola mata, menuang segala yang nampak tanpa tergesa-gesa. Malam ini, di puncak Gamalama yang gemilang, aku beradu kata bersama ilalang yang bernyayi atas nama Lara dan nama Tuhan.
Sungguh, diketinggian ini, aku dapat memaknai sendiri serendah mungkin. Melafazkan apa-apa yang tak sengaja diterka mata dengan kata-kata, pula berharap cemas pada rimba malam yang malu-malu untuk menikam. Di teras gubuk berhias bunga-bunga, aku duduk di atas dipan menghadap jauh pada dua pulau yang masih teka teki, menebak-nebak dengan kaku seraya menyeruput kopi pekat itu dari gelas bambu. Gemerlap lampu-lampu di pinggiran kampung itu terus menyala-nyala, tak ada hiruk pikuk yang mampu dijamah telinga, semua lelap pada sunyi-sunyi yang nyeyak.
Ilalang terus berzikir di balik semak-semak, gemulai air terjun di ujung tebing juga senada. Sebuah malam yang elegan, yang me-lelapkan jutaan insan di atas ranjang kayu sampai yang paling empuk, hingga mimpi-mimpi bertebrangan jadi ilusi juga misteri. Telah sepertiga malam merangkak, merambah bersama desiran angin utara yang amat dingin mengena tubuh, di puncak yang semilir ribuan dilema berlarian kencang di atas kepala, menghanyutkan dan menenggelamkan. Juga tentang sesosok yang bermuka manis, yang pernah ku temui di pinggiran halte, perempuan beralis tebal bernama Lara.
Di puncak Gamalama yang harum, yang bertabur wewangian daun pala dan cengkih, apa-apa yang ku rangkai dan ingin namun tandas kini kembali mampir menjadi penguat. Merayap serupa nyamuk-nyamuk yang menghinggap diselangkangan, lalu kemudian lenyap pada gelap-gelap yang juga adalah cahaya. Yang peling tekun melayang dari semua yang yang melayang dan mampir di isi kepala ku adalah Lara, perempuan beralis tebal itu. Ia yang paling kuat getarannya, seolah rumah hati ini adalah tempat bersemayamnya untuk meramu cinta yang sesungguhnya adalah titah.
Merebahkan tubuh sesekali, namun jemari tak juga memilih rehat untuk merangkai, jari-jari ku terus lincah menyerbu setiap huruf-huruf hingga terjahit menjadi bait tentang Lara. Menjadi puisi-puisi yang bernada sendu dan harap, yang tak redup pada duplikat yang gemar direnggut keasliannya. Replika subuh telah bergemuruh serupa nyayian lalayon, makin lama makin haru saja. Aku masih terbaring di atas dipan. Mereguk puncak dengan ribuan pengharapan yang melangit. Ingin ku sederhana, sesederhana mama mengenyam saloi dari kulit bambu, aku ingin menjumpai mu kembali, tapi bukan lagi di halte kampus.
Subuh telah usai, barang-barang bawaan telah aku kemas ke dalam tas. Mentari telah pecah dari arah ufuk, menebar terik dari sela-sela pohon besar yang mengahalau. Di ujung tangkai daun pala dan cengkeh embun mendekap dengan erat, membasuh dengan basahnya yang adalah subur. Aku keluar sebentar, menghirup udara dengan secangkir teh hangat bikinan sendiri sambil mengumpul bekas-bekas botol yang berserakan di sekeliling gubuk. Matahari telah merangkak pelan-pelan ke arah barat, aku telah berkemas untuk langsung bergegas berpulang. Di bawa keteduhan pohon-pohon perkasa dan pala serta cengkeh, sederet pengharapan tentang Lara hidup kembali setelah tidur sejenak di waktu subuh.
Aku pulang dengan semangat baru setelah menepi sehari di atas puncak Gamalama, Lara adalah salah seorang arah yang hendak aku temui nanti. Aku akan menjumpainya kembali dengan cara apapun, namun bukan lagi di halte kampus. Pagi berjalan terus, mentari telah di tengah dengan teriknya yang tak terkendali. Pada sebuah jenjang dari bebatuan, aku duduk bersandar dengan keringat yang mengalir, meneguk air secukupnya untuk sekadar membasahi kerongkongan. Burung-burung di sana seolah bernyayi, hingga gemuruh yang terjadi semacan nyayian juang para pemberontak yang mengiginkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Lagi-lagi Lara mampir disela-sela rehat panjang itu, ia mampir dengan alisnya yang tebal, dan juga mukanya yang manis.
Perjalanan pulang menuju kosan ku lanjutkan, dengan hati-hati aku menuruni jalanan Gamalam yang licin itu. Tak sampai sejam, akhirnya aku pun sampai di badan jalan, rehat sejenak dan merokok sebantar. Ingin ku menulis sedikit, namun napas terus tersengal-sengal menghantam otak. Aku hanya duduk meluruskan dua kaki sambil menunggu kawan ku menjemput, sejam beralalu, kawan ku tak juga datang. Terik matahari makin menyengat, ku seka keringat yang tak henti-henti membanjiri sekujur dengan sehelai kain yang ku sobek dari baju ku sendiri. Lara kembali berlarian di atas kepala ku, seolah wajahnya yang manis tak mau berpaling, juga alisnya yang tebal. Aku terus bertengkar dengan harap ku sendiri di pinggiran badan jalan bertemankan teh pucuk segar yang ku beli di warung tadi. Bunyi motor kawan ku telah ku dengar dari kejauhan, dari arah perempatan kawan ku muncul dengan wajah kaku dan senyum-senyum malu. Tanpa lama-lam kami pun berjalan pulang menuju kosan.
Hari berganti hari, minggu pun berganti. Aktivitas biasa yang selalu ku geluti kembali ku jalankan, pergi ke kampus, melapak bersama kawan-kawan, menulis di koran Malut Post, dan menulis puisi-puisi di beranda facebook. Tepat di hari Selasa yang ramai, juga pagi cerah dengan sepenggal harap yang berwarna, aku pergi begitu cepat ke kampus dengan tidak biasanya, hanya sekadar duduk bersama kawan-kawan untuk berdiskusi, dan setelahnya meminjam motor untuk pergi membeli koran. Di teras kantin, Lara duduk bersama dengan teman-temannya, mulutnya komat-kamit seolah mempercakapan sesuatu, entah itu tentang apa. Aku berdiri dan berjalan selangkah menjauh pada kawan-kawan, melihatnya dengan khusyuk tanpa tahu diri. Aku ingin mendekatinya, mengajaknya berbicara dan setelahnya pergi bersamanya membeli koran. Lara, pagi ini kau nampak manis dengan alis tebal mu yang tak kalah cantik, mentari mungkin malu menebar terik, sebab hari ini kau yang paling bersinar.
Lara, aku ingin duduk bersama mu, bercengkrama dengan mu perihal isi kepala ku yang adalah kamu. Alis tebal mu itu telah membikin ku hanyut terombang-ambing di antara laut yang bernama jatuh cinta dan rindu, Gamalama yang mengigatkan ku. Hari ini, kau ku lihat kembali di teras kantin dengan kebaya panjang berwarna hitam, dan juga hijab mu yang estetik kecokelatan. Lara, perkenalkan, namu ku Pram, lelaki setengah hati yang gemar menulis tentang mu di berandanya. Maaf, bila ku lancang dan alpa pada restu mu, namun kau juga tak bisa menghentikan jemari dan isi kepala ku yang sering bertengkar ini, kau adalah senja yang sering mampir dengan indah di langit Halmahera. Bolehkah aku berkenalan dengan mu.?, Akh, Lara, sungguh kau nampak anggung hari ini, sekali lagi, aku Pram, lelaki urak-urakan yang mencoba mencintai mu dengan menulis.
Oleh: Muhammad Hatta Abdan
“Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Khairun Ternate”










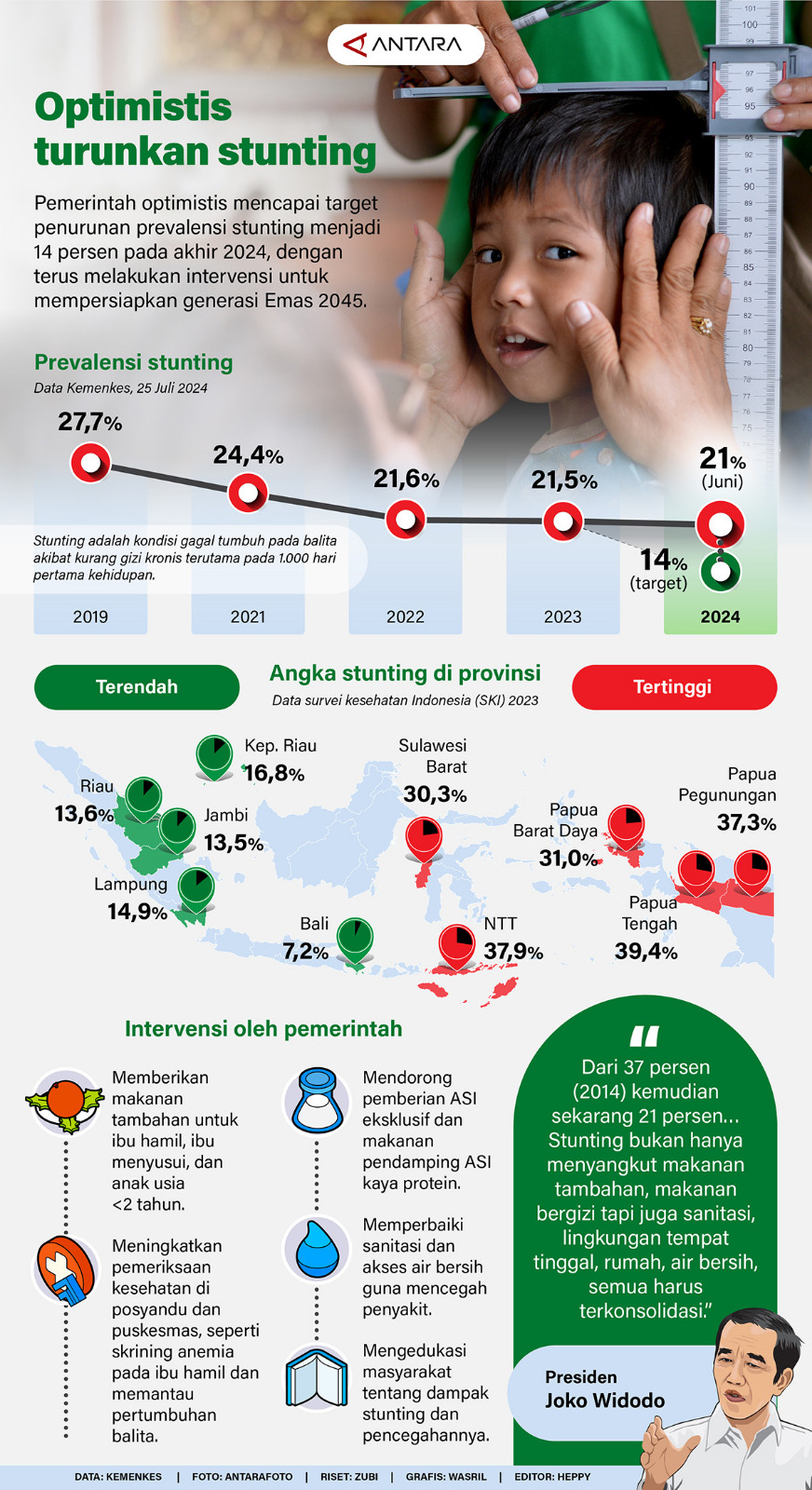

Discussion about this post