MEDIASEMUT.COM — Setiap momentum politik pesta demokrasi. Ruang publik selalu menjadi medan magnet untuk dijadikan bantu loncatan mendapatkan simpati publik. Peran propaganda antara kubu satu dan lainnya, berhasil menggiring opini masyarakat dalam menentukan, siapa yang akan dipilih. Bukan rahasia umum lagi, saling hujat di media sosial antara pendukung, sangatlah lumrah terjadi. Bahkan begitu memanas, yang melibatkan dari berbagai lapisan kelompok, baik itu kalangan intelektual maupun masyarakat awam. Hal itu tentu bisa disaksikan langsung menjelang momentum pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) serentak, di Indonesia setiap lima tahun sekali.
Di Maluku Utara, atmosfer politik menjelang pilkada 2024 cenderung sensitif. Masing-masing kandidat membangun pencitraan di antara masyarakat, bahkan di media sosial. Setiap Paslon (Pasangan Calon), baik itu Gubernur maupun Bupati, memanfaatkan ruang publik sebagai sarana yang signifikan untuk melancarkan sirkulasi pencitraan. Tujuan utamanya, tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki niat baik dalam kontestasi kali ini. Meski ada beberapa kandidat yang tentunya memiliki rekam jejak dalam memimpin, terpotret buruk di kalangan masyarakat. Seolah-olah dalam momentum kali ini, mereka muncul sebagai orang yang berbeda, walaupun watak dan perilaku tetap sama.
Maka perlu adanya bagi setiap orang, melakukan klasifikasi secara rasional dalam menilai pemimpin yang berlandaskan karakter serta rekam jejak para kandidat. Sebab banyak orang, termasuk orang yang menyandang legalitas intelektual berposisi dan memihak tanpa dasar yang rasional, bahkan cenderung menilai menggunakan kacamata kuda. Sehingga kali ini penulis, lebih memfokuskan pada aspek peranan intelektual yang juga turut andil dalam meramaikan pesta demokrasi. Dan fungsi esensial yang mestinya dilakukan pada momen-momen seperti sekarang. Sebagai sebuah refleksi fenomena pemilu serentak di Indonesia khususnya Maluku Utara.
Peran Dan Fungsi Intelektual
Intelektual secara harafiah diartikan sebagai orang yang cerdas, berpikir jernih, cendekia dan punya potensi pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Coser (1965), kaum intelektual adalah orang-orang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang oleh masyarakat sudah dianggap baik. Legalitas itu biasanya secara inheren dilabelkan pada ilmuan, akademisi, wartawan, mahasiswa maupun orang yang memiliki potensi kritis dan mencerahkan.
Dari definisi di atas, kita bisa berkonklusi bahwa intelektual selalu berpikir kritis terhadap fenomena sosial di ruang publik. Dan barang tentu memiliki formulasi pencerahan pada masyarakat sebagai upaya memecahkan masalah yang sering kali dianggap biasa-biasa saja. Namun, kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian intelektual selalu didikte oleh para elit politik hari ini. Sehingga kategorisasi intelektual dalam realitas sosial bisa dibedakan secara nyata.
Apalagi, momentum politik demokrasi kali ini, mereka benar-benar nampak dengan konfigurasi yang berbeda.
Antonio Gramsci (1891-1937), seorang pemikir asal Italia mengonsepkan intelektual sekaligus memberikan perbedaan secara holistik tanpa melihat latar belakang seseorang. Menurut Gramsci, intelektual terbagi atas dua kategori, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Pembagian tersebut tidak terlepas berdasarkan kondisi objektif dan relasi yang dibangun antara masyarakat dan negara. Merujuk pada pandangan Gramsci di atas, ia mendefinisikannya secara longgar.
Intelektual tradisional menurutnya adalah mereka yang bertugas menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, maupun para elite politik. Misalnya sebagai mediator untuk mengarahkan masyarakat atau orang lain, agar menyepakati ide-ide yang dikehendaki oleh mereka. Kaum intelektual jenis ini, sering kali memanfaatkan pengetahuannya untuk mendukung kelas penguasa. Mereka terkadang melacurkan independensi, demi kepentingan material dan posisi aman.
Sedangkan intelektual organik, mereka yang secara eksistensinya tidak terikat dengan barisan-barisan elite. Mereka menjaga independensi dari segi pengetahuan maupun ideologi dan lebih suka menentang kesewenang-wenangan. Bahkan tidak mau didikte demi kepentingan material apalagi untuk mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan dll. Intelektual jenis ini, paling sering melakukan penyadaran kepada masyarakat secara ideologi dan politik untuk memahami setiap kebijakan serta masalah-masalah sosial. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat. Menurut Vedi Hadiz, di Indonesia ini sudah terlalu banyak intelektual tradisional. Dan ironisnya, kita sangat kekurangan intelektual organik. Hal itu diakibatkan karena aktivitas dan orientasi mereka lebih sering menjadikan kebutuhan ekonomi yang berlebihan sebagai dalil untuk melacurkan pengetahuannya.
Dilema Intelektual Dan Demam Pilkada Maluku Utara Sebagai sebuah momentum sakral dalam menentukan arah atau kiblat tatanan sosial. Pesta demokrasi menjadi panggung masa depan yang dicita-citakan banyak orang. Perhelatan politik yang sarat akan beragam konsekuensi berkelanjutan. Kini makin memanas dalam manuver strategi merebutkan kepemimpinan dalam skala politik lokal. Pilkada yang notabene sebagai ajang perebutan kekuasaan, memang selalu menguras tenaga, pikiran, bahkan biaya. Pasalnya, setiap kandidat mati-matian berupaya untuk merebut kemenangan dengan cara apa pun. Itulah mengapa, pemilu berbiaya tinggi (high cost).
Di Maluku Utara, tensi politik yang memanas bukan saja pada taraf kabupaten, akan tetapi sampai pada tingkatan provinsi. Empat kandidat yang kini maju sebagai bakal calon Gubernur, telah menawarkan segudang janji pemanis di lidah. Uniknya tiga di antaranya adalah eks kepala daerah, di tiga kabupaten yang ada di Maluku Utara. Sudah barang tentu, rekam jejak mereka selama kepemimpinannya sebagai kepala daerah, telah dikantongi oleh sebagian besar masyarakat. Ada yang pernah menjanjikan 5000 lapangan pekerjaan, tetapi ketika terpilih, ribuan masyarakat keluar darah mencari kerja. Ada juga yang menjanjikan pembangunan jalan lingkar, tetapi selama periode kepemimpinan berakhir, akses jalan masih sangat memprihatinkan. Bahkan ada salah satu kandidat, ketika menjadi bupati pernah melepas tangan yang hampir terjadi pelelangan Pulau Widi dalam Sotheby’s New York.
Namun, di momentum pilkada serentak, mereka seolah-olah muncul sebagai wajah baru. Banner politik, media Online, halaman-halaman surat kabar, kini dipenuhi wajah-wajah Paslon dan segudang janji beserta jargon politik masing-masing. Meski memiliki rekam jejak yang buruk, mereka tentunya berhasil menyihir sebagian simpati publik. Sehingga ramai di media sosial, Facebook, Wa, Tik Tok, dan Instagram. Banyak pendukung fanatisme yang hendak membela kandidatnya bila beredar sebuah informasi yang kemudian menyinggung di salah satu kandidat.
Dari sekian perdebatan hangat di media sosial, cenderung melibatkan masyarakat awam. Hal itu mungkin kita bisa diakui bahwa, mereka belum memiliki pemahaman secara khusus terkait situasi politik secara rasional. Namun yang menjadi persoalannya adalah, keterlibatan intelektual baik itu akademisi maupun mahasiswa dan kelompok yang mencerahkan, bahkan ikut terjun meramaikan, bukan sebagai penengah tetapi pelaku. Mereka turut membela kandidat dengan ciri-ciri seperti di atas secara terang-terangan. Hal ini menunjukkan bahwa, dominasi dalam praktik kontestasi politik lokal selalu dipenuhi oleh kelompok intelektual tradisional.
Artinya bahwa, wilayah tersebut bukan berarti tidak bisa diintervensi. Setiap orang berhak menentukan pilihannya, siapa pun dia termasuk intelektual. Tetapi perlu dilihat dari rekam jejak dan bekingan partai. Dan harus dianalisis secara mendalam. Bukan berpihak pada mereka yang tidak memiliki komitmen nyata terhadap tujuan perbaikan sosial. Apalagi, dari semua visi misi, hampir tidak ada yang mendorong persoalan lingkungan dan ekologi. Padahal di Maluku Utara, isu ini menjadi sangat krusial untuk didorong, sebagai jalan keluar dari problem lingkungan selama ini. Karena hutan Halmahera, makin hari kian menipis akibat investasi oligarki. Tentu dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam. Sehingga sangat keliru bila ingin memberikan kesejahteraan, tetapi persoalan yang sangat menyentuh dengan masyarakat tidak didorong.
Maka tugas intelektual dalam pilkada, harusnya membuat narasi-narasi penyeimbang di tengah beredarnya pencitraan para kandidat terhadap janji-janji politiknya. Dan memberikan pendidikan secara ideologi maupun politik pada massa luas terhadap pemilu. Karena kampanye politik saat ini penuh dengan ujaran kebencian (hate peech), dan penyebaran informasi yang provokatif, yang dampaknya selalu menciptakan kegaduhan dan pertengkaran. Sebab, banyak orang terus diarahkan pada segmen politik yang berantakan seperti itu. Sehingga mereka terpaksa didorong untuk menyaksikan dan menyerap energi dari kegaduhan pada ruang-ruang yang tidak mendidik. Fakta itu terjadi pada setiap pemilu berlangsung di era kegemilangan teknologi modern.
Oleh karena itu, pentingnya seorang intelektual memahami posisinya dan membuat batas secara tegas dengan para kandidat dan elite politik hari ini. Sebab pengetahuan dan kecerdasan, tidak bisa digadaikan demi kepentingan sesaat. Apalagi menghalalkan segala cara, itu sangat memalukan. (*)
Oleh : Fikram Guraci
(Anggota SMI Cabang Ternate)










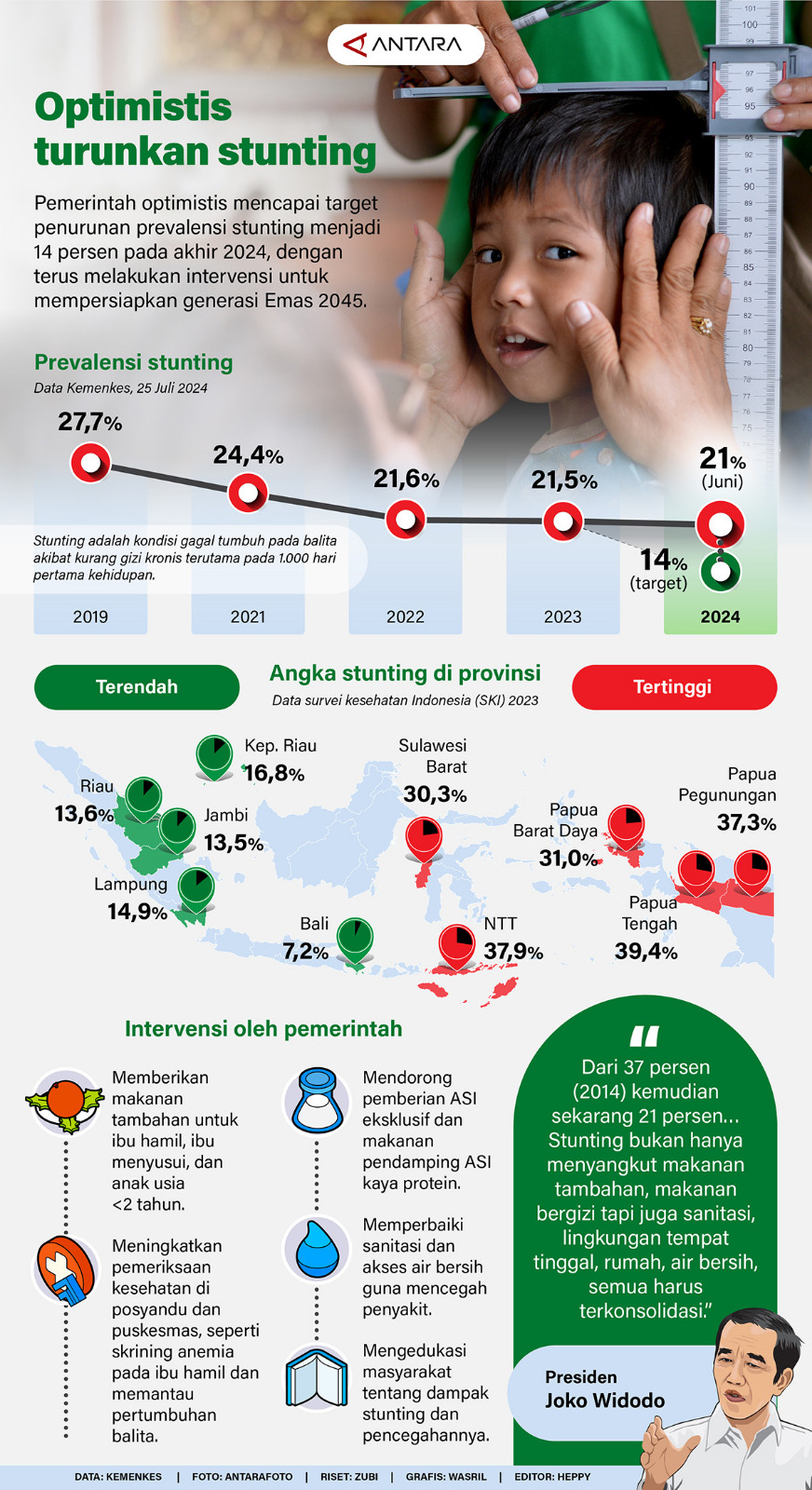

Discussion about this post