MEDIASEMUT.COM – Rutinitas saya di hari ini dibuka dengan salah satu lembaran Hilman Hariwijaya, pengarang yang buku-bukunya telah menemani saya semenjak sekolah dasar. Ia telah menghembuskan napas terakhir pada 09 Maret tahun lalu, setelah berjuang melawan penyakit liver. Senada dengan para netizen di hiruk-pikuknya Twitter, sampai hari ini saya pun merasa kehilangan, walau saya memang belum pernah bertemu, atau bahkan bersuasapa, dengan Hilman. Namun, pergulatan saya dengan Lupus Kecil, Rumpi Kala Hujan. Semenjak beberapa minggu belakangan ini membuat saya kembali menjadi bagian dari dunia Hilman dan Lupus.
Ya, saya memang sedang terlibat dengan sebuah proyek Proposal penelitian mengenai geografi dan ruang dalam sastra anak di dunia kesustaraan anak-anak. Beberapa bukunya saya pilih sebagai salah satu obyek penelitian karena kelincahan tangan dan pena Hilman dalam membangun dunia tempat Lupus tinggal, perpaduan antara dunia nyata dan imajinasi, antara imaji masa lalu yang penuh memori dan realita masa kini yang masih aktual. Ironisnya, nama Hilman dan Lupus sendiri sangat jarang disebut sebagai bagian dari khazanah sastra anak Indonesia. Justru, kelucuan atau di dalam buku ini yang membuat banyak orang tidak bisa menjajarkan Lupus dengan “sastra dalam satu kalimat.
Serial Lupus dianggap terlalu menjual kesenangan dan kelucuan tanpa nilai-nilai moral dan pendidikan yang sangat eksplisit. Hasilnya, Lupus dianggap setara dengan komik yang hanya menjual kesenangan dan dinilai tidak bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Jacqueline Rose dalam bukunya The Impossibility of Children’s Fiction (1986) menggugat kentalnya pemaksaan nilai-nilai orang dewasa dalam sastra anak dan mengabaikan kenikmatan (pleasure) yang seharusnya ada dalam proses pembacaan sastra. Di tahun 1992, Perry Nodelman menyebut sastra anak yang hanya berkutat dengan proses pendidikan moral untuk membentuk anak menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang dewasa sebagai salah satu bentuk penindasan atau kolonialisme. Mereka hanyalah dua dari banyak ilmuwan dan peneliti sastra anak yang menyuarakan kembalinya fokus kepada anak dalam karya sastra dan media yang memang ditujukan untuk mereka.
Inilah sastra anak yang seharusnya. Sastra yang ditulis dengan suara dan minat anak-anak. Teks yang bercerita tentang dunia dari kacamata mereka, bukannya dunia yang diinginkan orang dewasa untuk dialami anak-anak. Di sisi lain, serial Lupus sendiri bisa dikatakan melawan arus narasi yang dikibarkan oleh rezim Orde Baru tentang keluarga ideal. Pemerintahan Orde Baru, sebagaimana dituliskan oleh Julia Suryakusuma, senantiasa menggaungkan narasi keluarga ideal. Ayah diproyeksikan menjadi sosok dengan otoritas penuh untuk mengatur keluarga, sementara ibu jadi sosok penuh kasih yang mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat semua anggota keluarga. Tapi apa yang terjadi di dalam serial Lupus? Sosok Papi dan Mami justru sering sekali bertindak seperti anak-anak dengan kesalahan ataupun keisengan mereka yang tidak kalah dengan Lupus dan Lulu. Ketidaksesuaian penggambaran di buku ini dengan narasi pemerintah tentu saja menjadi alasan ketidakmampuan masyarakat melihat Lupus sebagai sebuah karya sastra yang setara dengan Siti Nurbaya atau Layar Terkembang.
Salah satu tujuan penelitian saya adalah untuk mengangkat Lupus dan Hilman, pengarangnya, ke jajaran karya sastra. Setidaknya, serial ini bisa mendapatkan apresiasi di dunia kesustaraan anak-anak apabila masyarakat Indonesia masih menolak mengakui posisi Lupus sebagai sebuah karya sastra untuk anak.
Sayangnya, Hilman sudah meninggal sebelum penelitian ini direncanakan. Yang bisa saya lakukan saat ini hanyalah menuliskan opini pendek dan berharap bahwa semakin banyak di antara kita yang bisa mengapresiasi Hilman dan karya-karyanya sebagai bagian dari khazanah kesusastraan anak Indonesia.
Oleh : Burhanuddin Jamal
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ISDIK Kie-raha Maluku Utara










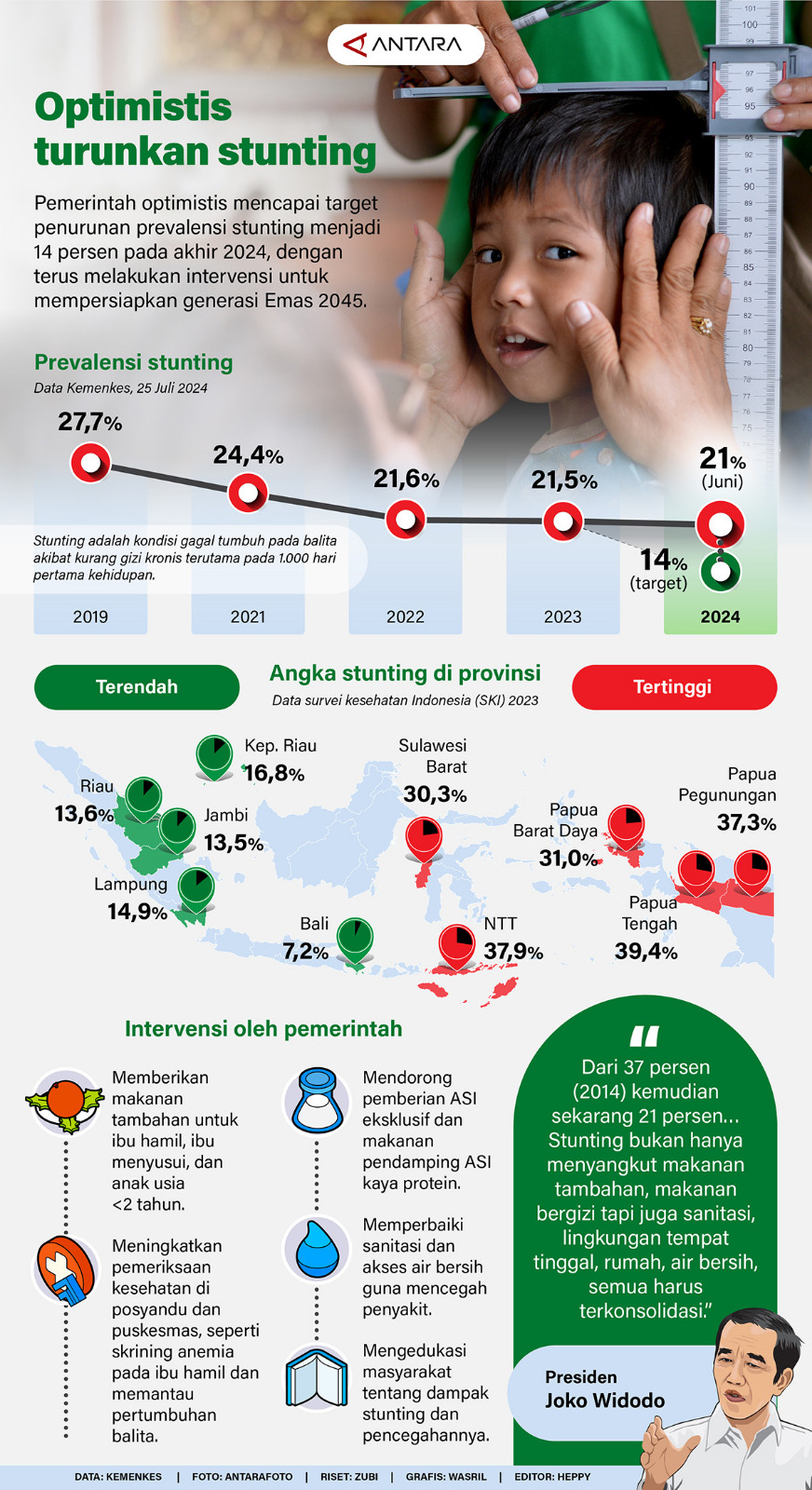

Discussion about this post